Bulan Untuk Bapak
Sang Pena - Sejarah selalu menyisakan kesan ketika dikenang. Sekalipun masa telah membentangkan jarak yang berkepanjangan antara masa lalu dan masa depan. Sebenarnya antara keduanya tidak pernah tersekat jarak. Selama ingatan masih kita simpan rapi di dalam ingatan. (alefiko)
Cerpen. Saya memang cukup lemah di bidang yang satu ini, tapi bukan berarti saya tidak mencoba untuk menulisnya. Sudah beberapa kali kok :) Tapi, ya itu, selalu kurang puas jika harus membaca karya sendiri.Walaupun demikian, ketidakpuasan itu adalah bukti dan sekaligus anjuran kepada diri pribadi untuk terus belajar. Menulis lagi tentunya.
Nah, berikut ini adalah cerpen yang pernah saya tulis beberapa tahun silam. Berharap masih bisa dibaca sekalipun jelek, berharap masih bisa dikritik sekalipun pembaca hanya penikmat tulisan. Yuk, silakan :)
Cerpen. Saya memang cukup lemah di bidang yang satu ini, tapi bukan berarti saya tidak mencoba untuk menulisnya. Sudah beberapa kali kok :) Tapi, ya itu, selalu kurang puas jika harus membaca karya sendiri.Walaupun demikian, ketidakpuasan itu adalah bukti dan sekaligus anjuran kepada diri pribadi untuk terus belajar. Menulis lagi tentunya.
Nah, berikut ini adalah cerpen yang pernah saya tulis beberapa tahun silam. Berharap masih bisa dibaca sekalipun jelek, berharap masih bisa dikritik sekalipun pembaca hanya penikmat tulisan. Yuk, silakan :)
“Bulan” untuk Bapak
Seperti
hari-hari yang lain, minggu-minggu yang lain, bulan-bulan yang lain, semenjak
aku kelas 3 SD, hingga detik ini, hampir setiap sore setelah shalat Ashar aku
akan berusaha menyempatkan datang ke tempat ini. Sebuah gubuk, agak reyot, di
belakang rumah tepat menghadap sebuah sungai di desa kecilku. Gubuk yang di
dalamnya telah kuabadikan begitu banyak kenangan. Di gubuk ini pula, dulu bapak
hampir setiap hari menceritakan masa mudanya, tentang pertemuan tak terduganya
dengan ibuku, tentang kakek yang hilang pada masa PKI, dan tentang kearifan
hidup dari beliau yang ku pendam dalam-dalam di dasar kalbuku. Hingga kini, dan
selamanya akan tetap berada di sana.
–—
Sore
ini, hujan telah reda dan telah undur diri bersama angin. Sebenarnya ini juga
merupakan hujan pertama di musim penghujan, aku paham betul dari aroma ampo[1]
yang begitu semerbak menyejukkan yang telah kukenal bertahun-tahun hidup di
sini. Hujan pertama yang bagiku begitu menentramkan setelah panas
berkepanjangan, tentu saja. Kadang aku berfikir hujan tadi sebagai obat
meradangnya bumi ini atas ulah manusia yang sak
senengé déwé[2],
yang mengeksploitasi sumber daya, mengaduk-aduk isi bumi untuk kepentingan perut
segelintir orang saja, bukan untuk kepentingan anak-cucu ibu pertiwi kelak.
Andai bisa bicara, mungkin bumi akan melakukan jumpa pers, batinku sesekali. Atau
mungkin memanggil sekutu untuk melawan manusia seperti di film-film. Ah
sudahlah, kiranya aku terlalu banyak menonton film fiksi.
Aku
berjalan tanpa alas kaki menuju gubuk. Berjalan pelan sambil menikmati detik-detik
yang mengingatkanku pada sosok bapak, perasaan anak kepada bapak yang
dirindukan, perasaan yang masih butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Rasanya
aneh saja berjalan sendirian di sini. Biasanya beliaulah yang menjadi rekan
seperjalanan menuju gubuk tersebut, sepanjang hidupnya. Kini tinggal diriku
yang menjadi pengunjung setia, mungkin suatu saat aku akan mengajak anak-anakku
ke sini, menceritakan padanya tentang Sang Kakek yang gagah berani, tentang
perjuangan hidup untuk keluarganya. Tapi, ah mungkin itu terlalu jauh. Aku
masih belum berfikir kesana sebelum studi Masterku selesai.
Aku
semakin dekat, gubuk ini tak seperti dulu lagi. Beberapa tiangnya terlihat mulai
miring, menyalahi aturan konstruksi. Atapnya, anyaman alang-alang yang dulu
rapi dan rapat (dulu kubuat bersama bapak, setelah seharian mencari alang-alang
di hutan perbatasan Ngawi) kini tak lebih dari bambu tua yang tersisa, itupun
kelihatan rapuh sekali. Akhirnya sampai, ku sentuhkan jari-jemariku di tiang
terdekat, aku merinding, ku pandang lagi sekeliling gubuk ini, hampir tak ada
yang berubah. Di sebelah kanan, agak ke kiri sedikit sebuah pohon mangga yang sudah
cukup umur sampai enggan berbuah manis. Biasanya setelah hujan akan banyak burung prenjak yang menghabiskan sorenya di
sana, diujung tertinggi, saling berebut perhatian. Tak berbeda dengan sore ini,
saat kutengadahkan ke atas, beberapa prenjak memang sedang dimabuk cinta, atau
mungkin mereka juga merindukan kedatanganku disini setelah lama sekali
penantian atas diriku, dan inilah reuni kami, lintas generasi makhluk Allah. Homo Sapiens – Prenjak.
Di
sebelah kiri gubuk, di sanalah pekarangan kami yang dulu dijual untuk
pengobatan bapak. Luasnya tak seberapa, namun cukup untuk membantu meringankan
beban kami saat itu, tapi kini hanya tanah tandus tak terawat, aku bahkan tak
pernah tahu siapa pembelinya. Dan di depan, tepat di depanku saat ini, terlihat
dengan begitu anggun, meliuk-liuk sebuah sungai mirip “naga berwarna coklat”
(karena air yang keruh, tentu saja) yang sangat terkenal dengan diciptakannya
lagu untuk sungai ini oleh Alm. Gesang, “Bengawan Solo”.
Aku
duduk, menurunkan tas punggungku, terdengar bunyi berderit. Aku hanya tersenyum
simpul, mungkin beban tubuhku saat ini sudah jauh melampaui beban terakhir saat
aku duduk di sini, beberapa tahun yang lalu.
Seperti
tahun-tahun dan hari yang lalu, jika aku ke gubug ini aku akan selalu menyempatkan
diri untuk menulis sesuatu, apapun. Karena menurut bapak perintah Iqra’ dalam
Al Qur’an tak hanya untuk membaca, melainkan lebih luas lagi, termasuk menulis
dan beramal. Dan bagiku, ucapan-ucapan beliau adalah permata yang harus
dilaksanakan selain itu di sinilah tempat yang memberiku inspirasi untuk selalu
menulis. Aku keluarkan partner
favorit untuk menulis dari dalam tas punggungku tadi, sebuah Laptop. Merogoh
dompet kecilku, lalu ku ambil KTP beliau yang kusimpan rapi, ku pandang wajah itu
dalam-dalam, wajah yang lelah dan bertanggung jawab semasa hidupnya, tak terasa
titik-titik kecil dari mata ini mendesak keluar, tak bisa kutahan. Ku pejamkan
mata sejenak, lalu sekelebat wajah beliau dengan senyumnya mendadak muncul di
kepalaku. Aku rindu, benar-benar rindu. Tanganku mulai mengetik, sebuah puisi.
Bersama anak panah
Yang meluncur ke bulan dari kedipan jiwaku
Ku sampaikan bait rindu akan hadirmu
Lewat kata yang tak terucap
Lewat hati yang teramat sepi
Beriring bintang dalam kemukus
Tentang bulan, bagimu yang benderang
Matahari bak lentera pertiwi
Demi malam yang menelan siang
Demi pagi yang merindukan senja
Sungguh bulan adalah karunia
Karena malam,
Engkau ajarkan aku tentang bulan
Tentang waktu dan kebijaksanaan
Demi waktu
Demi raja batara kala yang baru
Buatkan aku hari yang baru
Agar tidak ada lagi nikmat-Mu yang kudustakan
Kemudian
aku menyimpannya dengan sebuah nama “Bulan”
untuk Bapak. Semoga pilihan judul ini tidak salah, inilah belajar, begitu
aku selalu berpedoman.
Aku
hampir lupa kalau hari sudah semakin sore, sudah saatnya aku kembali. Aku harus
kembali lusa karena senin depan sudah masuk lagi. Selamat tinggal, suatu saat
aku pasti kembali ke sini, pasti. Seperti kepastian akan datangnya kematian,
seperti itulah aku akan selalu datang menujumu.
Baru
saja berjalan beberapa langkah, HPku bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari
nomor yang belum kusimpan. Isinya “Jika kamu dapat memimpikannya, kamu dapat mewujudkannya – Walt
Disney”. Aku hanya tersenyum geli
membacanya, tapi tentu saja membenarkan. Sambil menggeleng aku menengok sekali
lagi ke belakang, tersenyum, gubuk yang luar biasa. Dalam setiap langkah yang
kuayunkan berikutnya, semua terasa ringan. Aku pasti bisa.
[1] Tanah
(Jawa)
[2]
Sekehendak hati
Cerpen ini selesai ditulis pada tanggal 14 Juni 2011
Repost di Blog Sang Pena
17 Februari 2014 - Setelah tiga tahun tersimpan rapi di memori
Dibaca dimana sadja, boleh.
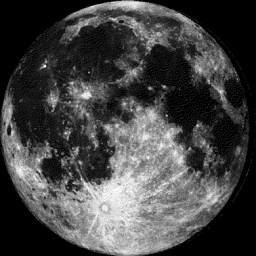



Comments
Post a Comment
Silakan tinggalkan komentar, yang sopan ya :) | Semua komentar akan dimoderasi.
Hendak diskusi dengan penulis, silakan via email di pena_sastra@yahoo.com. Terima kasih